OPINI
08 Oktober 2021
15:00 WIB
Memotret Realitas Ala Sineas
Parasite dan Squid Game tak cuma punya kesamaan dalam hal viral di kalangan warganet. Keduanya juga punya satu isu yang jadi fokus, yakni dualitas si kaya dan si miskin.
Penulis: Novelia
Sejumlah orang berjaket hijau dengan muka kelelahan, perlahan-lahan melompati satu per satu kaca untuk menyeberangi suatu jurang. Dalam tiap langkah, mereka harus memilih satu di antara dua kaca sebagai tempat mendarat.
Jika salah memilih—seperti Russian Roulette— kaca tersebut akan retak seketika dan membuat mereka terlempar ke jurang. Siapapun yang jatuh akan tereleminasi dari permainan sekaligus berakhir hidupnya.
Sadis? Pastinya. Inilah salah satu adegan dalam permainan pada Squid Game, sebuah serial 9 episode asal Korea yang diluncurkan Netflix dan berhasil membetot perhatian banyak penonton.
Dikisahkan, pertaruhan menegangkan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Peserta yang berhasil menjuarainya dan mengalahkan semua lawannya dari sejumlah permainan, berhak membawa pulang uang tunai 45,6 miliar won, setara dengan Rp555 miliar.
Uang sebesar itu, sudah pasti ini jadi tawaran menggiurkan. Sekalipun peserta harus melakukan pertarungan berdarah layaknya seorang gladiator. Penyelenggara permainan memang sudah secara spesifik memilih peserta-peserta yang terdesak membutuhkan banyak uang, karena terlilit utang atau memenuhi sejumlah kebutuhan.
Baca juga: Menggantang Senang dengan Uang
Di sisi lain, ketika nyawa para peserta jadi jaminan dalam permainan survival, beberapa orang yang masuk kategori VIP justru menganggapnya tak lebih dari lelucon. Di balik medium monitor besar, mereka duduk santai di sofa lebar yang nyaman. Makanan dan minuman ditawarkan oleh para pelayan sembari mereka tertawa-tawa menonton “perlombaan” tersebut.
Mengulang Parasite
Usut punya usut, ternyata permainan yang diikuti para “orang miskin” dalam seri Squid Game ini disponsori oleh para “orang kaya” yang tidak lagi tahu bagaimana mesti menghabiskan uangnya, demi merasakan kebahagiaan. Lagi-lagi Korea seakan memberikan kita gambaran jelas, bagaimana berjenjangnya posisi si miskin dan si kaya.
Ya, lagi-lagi. Karena sebelumnya isu ini juga dengan meyakinkan diangkat oleh negeri ginseng tersebut pada film Parasite yang sukses besar pada 2019.
Sekadar mengingatkan, Parasite mengisahkan keluarga Kim yang hidup serba kekurangan, melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Suatu hari, mereka melihat kesempatan untuk bekerja dalam sebuah keluarga Park yang kaya raya namun naif. Berbekal sejumlah tindakan penipuan, seluruh anggota keluarga Kim akhirnya dipekerjakan oleh keluarga Park yang tak tahu menahu identitas mereka sebenarnya.
Selaku sutradara, Bong Joon Ho berhasil menampilkan kontras yang sangat kentara antara si miskin dan si kaya dalam berbagai latar tempat maupun adegan. Sisi unik kehidupan yang diangkat dalam film ini pun, mampu membawanya sebagai Film dengan Bahasa Non-Inggris pertama yang sukses menyabet Piala Oscar.
Menariknya, dua tahun kemudian, isu kesenjangan ini kembali diangkat dalam karya sinema yang berasal dari negara yang sama. Apakah ada hubungannya?
Meski lewat alur kisah yang berbeda dari Parasite, nyatanya Squid Game juga mengulas permasalahan terkait pemisahan sosial antara masyarakat miskin dan kaya. Dugaan bisa saja mengarah, para penggagas seri Netflix ini sekadar ingin mengekor sukses Joon Ho dengan mencuil isu serupa.
Akan tetapi, di sisi lain, bagaimana jika ini memang cara para sineas Korea merepresentasikan salah satu permasalahan di negaranya?
Meski berpredikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia, nyatanya Korea Selatan punya sisi gelapnya sendiri. Jurang yang dalam memisahkan masyarakat berdasarkan kelas ekonomi sosialnya.
Warga yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan sering menyerah untuk mendapat tempat tinggal dan penghidupan yang layak, mengidentifikasikan diri sebagai “sendok kotor”. Di sisi lain, keluarga kaya diibaratkan sebagai “sendok emas”.
Demi bertahan hidup, si sendok kotor mesti rela melakukan apapun. Tak terkecuali, menggantungkan hidup dari para sendok emas. Kondisi ini setidaknya ditunjukkan oleh hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga kesehatan Korea yang berafiliasi dengan pemerintah pada 2019.
Tercatat, lebih dari 85% responden merasakan adanya kesenjangan pendapatan yang sangat besar di masyarakat. Sejumlah responden tersebut juga menilai bahwa orang-orang butuh hidup dari keluarga kaya untuk menjadi sukses (Shin, 2020).
Data tersebut cukup menggambarkan masih eksisnya masyarakat kelas bawah yang kesulitan menghasilkan uang dari hari ke hari di negara ini. Sangat kontras, setidaknya di balik dunia hiburan dan perekonomiannya yang nampak cemerlang jika dilihat dari kornea penduduk global.
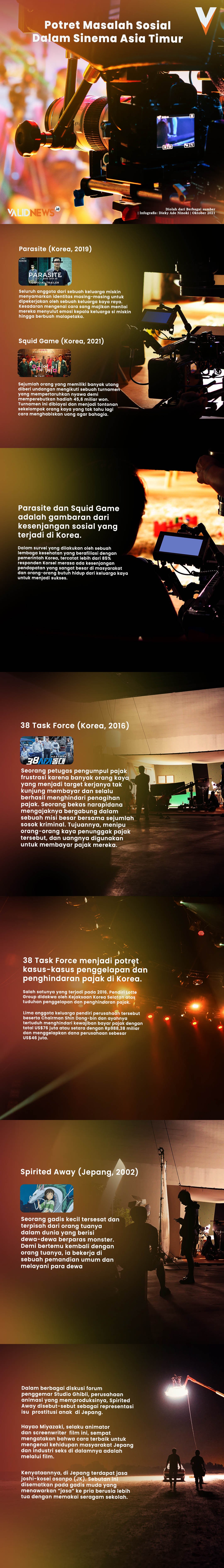
Pajak dalam Drakor
Tak cuma kesenjangan sosial dalam masyarakatnya, sineas Korea juga sempat memotret seriusnya permasalahan pajak dalam sebuah tayangan televisi. Seri drama yang digawangi Ma Dong Sok, Seo In Guk, dan Soo Young SNSD ini berjudul 38 Task Force.
Diramu dalam 16 episode, 38 Task Force mengisahkan seorang petugas pengumpul pajak yang frustrasi. Pasalnya, sejumlah figur kaya raya yang menjadi target divisinya tak kunjung membayar dan selalu berhasil menghindari penagihan pajak.
Di tengah kekalutan, seorang bekas narapidana mengajaknya bergabung dalam sebuah misi besar bersama sejumlah sosok kriminal. Tujuannya out of the box, menipu orang-orang kaya penunggak pajak tersebut, dan uangnya digunakan untuk membayar pajak mereka.
Kebetulan atau tidak, pada 2016, tahun yang sama ketika drama itu ditayangkan, sebuah kasus terjadi. Pendiri Lotte Group didakwa atas tuduhan penggelapan dan penghindaran pajak oleh pihak Kejaksaan Korea Selatan (Klinik Hukum, 2016).
Total tertuduh sebenarnya sebanyak 22 orang, meliputi mantan petinggi perusahaan maupun yang masih aktif. Termasuk, di antaranya pendiri Lotte Shin Kyuk Ho dan Chairman Shin Dong Bin.
Lima anggota keluarga pendiri perusahaan ini, bersama Shin dan ayahnya, dituduh telah bersama menghindari kewajiban bayar pajak dengan total US$76 juta, atau setara dengan Rp988,38 miliar. Mereka juga menjadi tertuduh penggelapan dana perusahaan sebesar US$46 juta.
Kasus Lotte ini hanya salah satu contoh kasus penghindaran pajak di Korea. Diketahui, sejumlah sosok petinggi perusahaan-perusahaan besar juga sempat terseret masalah serupa.
Mantan CEO Korean Air, Cho Yang Yo misalnya, memiliki catatan tuduhan menghidari pajak pada tahun 2000, serta menggunakan dana perusahaan untuk merenovasi rumah pribadinya pada 2013 dan 2014.
Pada 2018, Cho kembali diduga manghindari pajak warisan sebesar 50 miliar won, dan gagal melapor ke otoritas pajak terkait aset finansial di luar negeri yang jumlahnya hampir 1 miliar won.
Pada tahun yang sama juga, 2018, LG Group di Seoul pun disebut-sebut terlibat dalam aksi yang tak begitu berbeda. Beberapa kasus ini memperlihatkan bagaimana isu penghindaran pajak oleh orang kaya dan punggawa perusahaan ternama, menjadi isu serius di Korea. Dalam hal ini, 38 Task Force sebagai karya sinema, berhasil memotretnya dengan baik dan apik.
Kritik Sosial Animasi Miyazaki
Lain di Korea, lain di Jepang. Lewat medium animasi, Hayao Miyazaki juga menuangkan keprihatinannya pada berbagai masalah sosial. Salah satunya tergambar dalam Spirited Away, sebuah film animasi yang sudah banyak meraih penghargaan sejak penayangan perdananya pada 2002.
Ceritanya, seorang gadis cilik terpisah dengan kedua orangtuanya dan tersesat di sebuah dunia yang dipenuhi dewa-dewa berparas monster. Untuk bertemu kembali dengan orangtuanya itu, gadis bernama Chihiro itu harus bekerja di sebuah pemandian umum, melayani para tamu yang berkunjung untuk mandi.
Sejumlah hint dalam film ini menunjukkan eratnya kisah ini dengan fenomena prostitusi anak. Misalnya, bagaimana dalam film tersebut Chihiro diberikan nama panggilan baru sebelum bekerja di pemandian. Ini hal yang umum dilakukan dalam kalangan bisnis prostitusi Jepang (Anya, 2020).
Nama penggilan baru Chihiro di sana adalah Sen yang jika ditulis dalam huruf kanji berarti 1000. Hal ini pun diyakini banyak penggemar Studio Ghibli sebagai angka yang menunjukkan harga dari “jasa” yang diberikan Chihiro, yakni 1000 yen.
Panggilan tersebut serasa cocok buatnya, jika dikaitkan dengan profesinya sebagai “yuna” yang secara harfiah berarti “gadis pemandian”. Di negeri matahari, kata ini kerap dipakai untuk mengilustrasikan perempuan yang bekerja di pemandian umum dan harus memandikan dan memijat kliennya. Tak jarang pula berujung ke pelayanan seksual.
Studio Ghibli selaku produsen Spirited Away, memang tak pernah secara resmi mengamini bahwa prostitusi anak adalah fenomena yang mengilhami film ini. Namun, Hayao Miyazaki yang menjadi animator dan screenwriter-nya sempat menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengenal kehidupan masyarakat Jepang dan industri seks di dalamnya adalah melalui film.
Yap, dalam kenyataannya seks memang sudah jadi semacam bisnis di Jepang. Terkait pemandian umum sendiri, sejarah menyebutkan, dahulu ada beberapa pekerja seks yang melayani pelanggan di tempat-tempat tersebut. Industri ini bergulir sampai akhirnya disetop oleh polisi pada zaman Edo.
Sejarah boleh saja berlalu. Namun, faktanya hingga kini masih kerap terjadi prostitusi terselubung. Ironinya, sebagian dilakukan oleh perempuan berusia anak atau di bawah umum.
Sebuah dokumenter investigasi pernah membongkar bisnis joshi-kosei osanpo alias JK yang ada di Akihabara (Tempesta, 2015). Sebutan JK disematkan pada gadis muda, yang menawarkan sejumlah jasa ke pria berusia lebih tua. Biasanya, jasa yang ditawarkan di muka sebenarnya sekadar menemani mengobrol dan fortune telling.
Namun, jasa-jasa yang terlihat “aman” tersebut, kerap berujung menjadi layanan seksual. JK umumnya adalah anak-anak sekolah. Mereka pun menggunakan seragam ketika menjajakan “jasa”-nya.
Bukan tanpa alasan, memang para klien sendiri yang menyukai tampilan polos dari anak sekolah. Tanpa riasan yang berlebihan, dan rok seragam mini khas sekolah.
Ngeri-nya, jalanan tempat para JK menawarkan layanan mereka punya letak yang tak begitu jauh dari pusat kepolisian terdekat. Namun, seperti sudah jadi rahasia umum, fenomena ini terus berjalan tanpa penindakan berarti.
Tak heran, meski tidak sepenuhnya mengiyakan bahwa karyanya terinspirasi dari isu terkait, Miyazaki melihat permasalahan prostitusi anak sebagai hal genting di negerinya.
Sinema dan Realitas
Berbagai contoh yang sebelumnya dijelaskan, memperlihatkan bahwa sebuah produk sinema dapat menjadi medium tersendiri untuk memotret permasalahan atau isu di suatu tempat. Agak berbeda dengan beberapa sinema asal negara-negara Eropa yang lebih menonjolkan kemampuan teknologi dan pemain papan atasnya, sinema-sinema asal Asia Timur kerap membuat kita berdecak kagum dengan pemilihan kisah yang menyentil masalah sosial dalam realitas sekitar.
Faktanya, realitas dan karya sinema memang memiliki hubungan yang sangat erat. Keberadaan keduanya berdampingan dan saling memengaruhi. Sebuah produk sinema dengan pesan yang mendalam, akan memengaruhi para audiensnya sehingga tak butuh waktu lama untuk teraplikasi dalam realitas. Sebaliknya, realitas sendiri kerap menjadi inspirasi para sineas dalam memproduksi sebuah karya.
Menurut Budi Irawanto (1999), banyak studi mengenai dampak film yang menunjukkan, hubungan antara film dengan masyarakat selalu dipahami secara linear. Hal ini berarti film selalu memengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan isi pesan di dalamnya, tanpa berlaku sebaliknya. Namun, logika ini melahirkan kritik karena menempatkan audiens dalam posisi yang pasif.
Padahal, film atau produk sinema lainnya bisa jadi adalah potret dari masyarakat di mana ia dibuat. Sinema menggambarkan realitas yang hadir dan berkembang dalam masyarakat lalu diproyeksikan dalam layar.
Jadi, hubungan yang terjadi tak sekadar linear, namun juga pencerminan atau refleksi realitas. Sebagaimana produk sinema merupakan salah satu bentuk dari media massa.
Status sinema sebagai media massa juga lah yang kemudian menjadikannya punya daya tarik tersendiri di hati para audiens. Pasalnya, seperti yang dikatakan oleh Garth Jowett dan James M. Linton (1983), dapat disepakati, media massa punya kapabilitas merefleksikan masyarakat. Hal ini karena medium ini dituntut oleh lingkungan komersial untuk menyajikan konten berkualitas yang nantinya akan diterima oleh masyarakat luas.
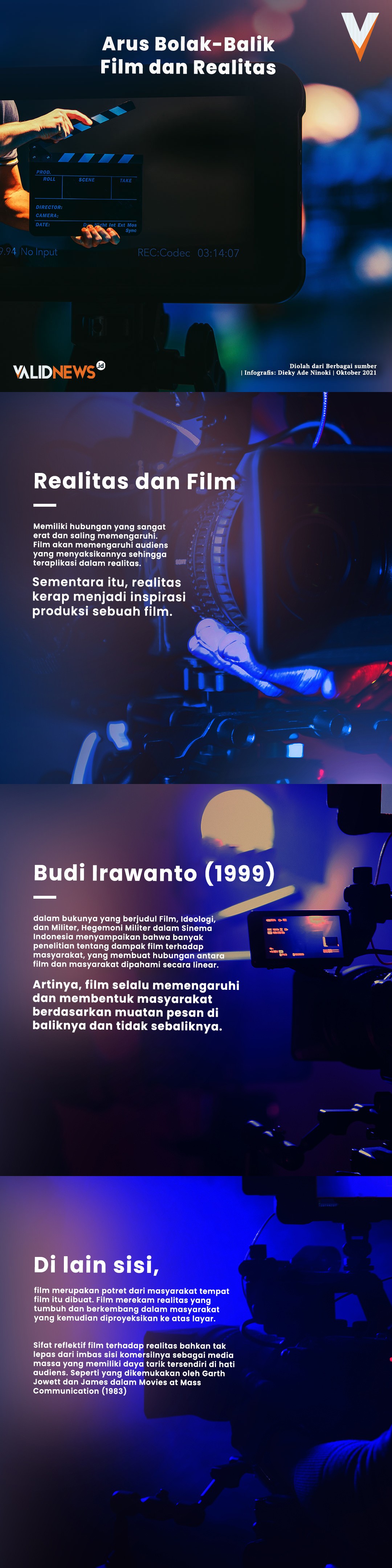
Pada akhirnya, fenomena karya sinema—bisa dikategorikan media—dijadikan medium untuk memotret masalah sosial menjadi hal yang positif. Sebab, menurut Bennet (dalam Hidayat, 1997) media tuh bukan cuma sekadar saluran pesan, namun juga merupakan subjek yang mengonstruksi realitas, bias, pandangan dan pemihakan. Jadi, kalau produk sinema berinisiatif mengangkat permasalahan sosial tertentu, apalagi sampai bersifat viral, masyarakat akan lebih peduli.
Ketika masyarakat sudah menyadari masalah tersebut, bukan tak mungkin akan ada desakan pada pihak berwenang untuk mengatasinya. Toh kini tak sedikit pergerakan-pergerakan kesetaraan yang berawal dari viralitas di berbagai media daring. Sarana untuk menghimpun suara kepedulian pun tak lagi satu-dua jumlahnya.
Sineas Jepang dan Korea telah bergerak menyentil para oknum yang terkait dalam masalah sosial di wilayahnya masing-masing dengan karyanya. Negara kita sendiri, Indonesia, bukannya tidak punya isu sosial yang butuh dibereskan.
Jika negara-negara Asia Timur tadi memilih memanfaatkan industri hiburan untuk menyadarkan ketidakberesan dalam masyarakatnya, apakah strategi kita? Jangan-jangan, kita terlalu bingung memilih fokus dari sekian banyak masalah yang terjadi.
Atau, jangan-jangan, apa yang dianggap suatu problema di luar sana, sudah dianggap hal biasa di sini dan tak menarik lagi untuk diangkat.
Referensi
Anya. (2020, Juni 5). Prostitusi Anak, Makna Tersembunyi di Film Spirited Away Studio Ghibli? Retrieved Oktober 5, 2021, from Japanese Station: https://japanesestation.com/anime-manga/anime/prostitusi-anak-makna-tersembunyi-di-film-spirited-away-studio-ghibli
Hidayat, D. N. (1997). Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi. Jurnal ISKI: Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Irawanto, B. (Yogyakarta). Film, Ideologi, dan Militer, Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia. 1999: Media Pressindo.
Jowett, G., & Linton, J. M. (1983). Movies at Mass Communication. Beverly Hills: Sage Publication.
Klinik Hukum. (2016, Oktober 20). Lotte Dihantam Kasus Penggelapan dan Penghindaran Pajak. Retrieved Oktober 5, 2021, from Klinik Hukum: http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+lotte+dihantam+kasus+penggelapan+dan+penghindaran+pajak
Shin, H. (2020, Februari 10). 'Parasite' reflects deepening social divide in South Korea. Retrieved Oktober 5, 2021, from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-awards-oscars-southkorea-inequality-idUSKBN20414L
Tempesta, E. (2015, Juli 20). Daily Mail. Retrieved Oktober 6, 2021, from 'People think it's role-playing. It's not.' Documentary lifts lid dark Jpan's schoolgirl culture reveals teen students forced prostitution obsessive older men: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3168563/Documentary-lifts-lid-dark-Japan-s-schoolgirl-culture-reveals-teen-students-forced-prostitution-obsessive-older-men.html





