OPINI
06 Oktober 2025
15:30 WIB
Analisis Kuasa Lokal, Faktor Penentu Implementasi NbS Di Sungai Sayang
Studi dari Pusat Studi Perdagangan Dunia – UGM, didukung FINCAPES, menemukan hal menarik dari peristiwa penebangan sekitar 110 hektare di Sungai Sayang Kecamatan Sadu yang mengagetkan masyarakat.
Penulis: Amin Tohari
Editor: Novelia
Foto udara saat warga berjalan di tepi Pantai Sungai Sayang, Sadu, Tanjungjabung Timur, Jambi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan.
Pada tahun 2022, sekitar seluas 110 hektare hutan mangrove di Sungai Sayang Kecamatan Sadu ditebang. Kejadian ini mengagetkan banyak orang, sekaligus membuat mereka bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa hutan mangrove seluas itu dibabati?
Studi dari Pusat Studi Perdagangan Dunia – UGM, yang didukung FINCAPES, mengenai upaya penerapan nature-based solution untuk mengatasi bencana ekologis yang terjadi di daerah tersebut mengungkap beberapa hal menarik dari rangkaian penebangan itu. Studi tersebut menemukan bahwa proses environmentalisasi NbS tidak dapat ditumpukan semata-mata pada pendekatan saintifik dan kebijakan. Proses ini juga harus mempertimbangkan dinamika relasi kekuasaan lokal, memahami proses perubahan sistem mata pencaharian, dan mendalami karakter perubahan biofisik setempat.
Mengurai Persoalan Kehilangan Mangrove
Pada temuan yang pertama, hal itu terkait dengan persoalan tenurial. Titik lokasi hutan mangrove yang ditebangi itu berada di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di luar kawasan hutan. Berbeda dengan hutan mangrove yang berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat melalui BKSDA dan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS), daerah APL secara fleksibel bisa digunakan untuk berbagai penggunaan.
Temuan yang kedua, selain statusnya yang APL, ternyata juga ada proses sosial ekonomi yang memicu dan mengembangkan proses privatisasi lokal yang kemudian mendorong alih fungsi mangrove secara lebih cepat. Proses privatisasi hutan mangrove ini didorong oleh investasi pembangunan pelabuhan di Ujung Jabung, meskipun rencana ini baru berjalan dan berhenti karena terhambat anggaran dan birokrasi yang rumit.
Tetapi, pada temuan yang ketiga, proses privatisasi ini juga terjadi dan dimungkinkan karena adanya sistem tata kelola sumber daya setempat yang sejak awal terbentuknya diatur oleh peran utama para kepala parit. Sungai Sayang adalah desa yang muncul dan berkembang dari migrasi para pelaut Bugis. Mereka membuat parit-parit sebagai sarana transportasi orang-orang dan hasil kebun. Tata pemukiman dan susunan pembagian kebun kelapa mengikuti kesepakatan para kepala parit.
Selanjutnya, temuan yang keempat, pada perkembangan lebih lanjut ketika desa harus masuk dalam administrasi negara, kepala desa yang menjabat seringnya adalah bagian dari kepala parit atau keturunannya. Mereka dianggap keluarga pendiri desa dan tahu tentang bagaimana sumber daya desa dikelola.
Salah seorang mantan kepala desa menggunakan legitimasi keturunan kepala parit dalam klaim penguasaannya terhadap hutan mangrove, yang ia perkuat dengan surat keterangan tanah di masa lalu. Bukti ini semacam menimbulkan rasa keberhakan baginya atas hutan mangrove, termasuk mengubah penggunaannya.
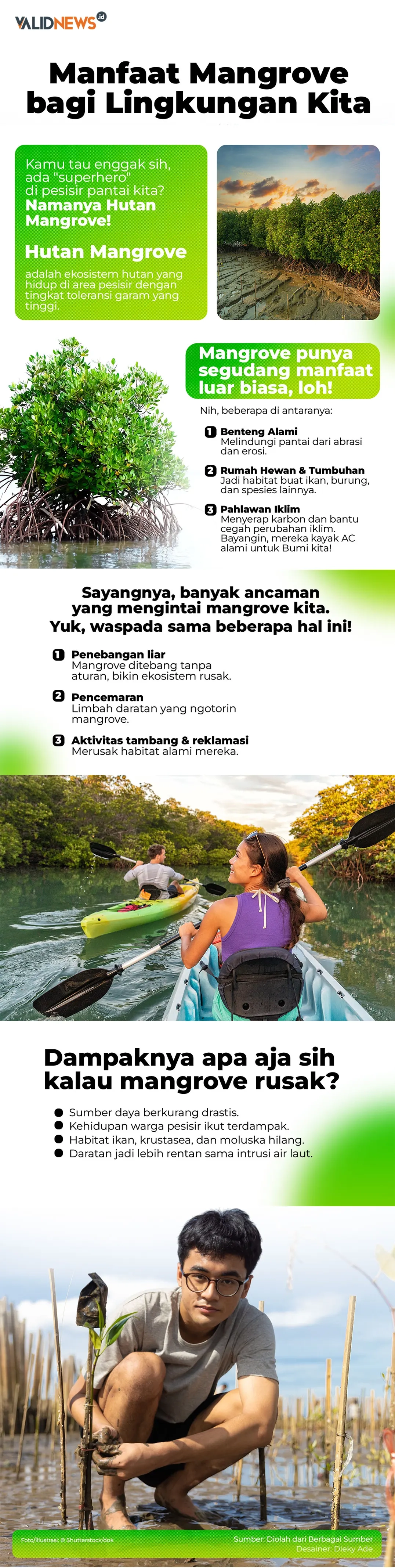
Temuan yang kelima, hal yang juga menarik kami temukan adalah seharusnya bagi masyarakat pesisir, mangrove merupakan salah satu ekosistem penting yang harus dilindungi. Namun, di Sungai Sayang tidak demikian. Tidak seperti pada masa lalu, ketika mangrove masih dianggap berfungsi sebagai penahan gelombang, sekarang, meskipun hidup di pesisir, masyarakat sudah tidak melihat mangrove sebagai sesuatu yang penting. Ini karena dalam 20 tahun terakhir, jumlah orang yang hidup dari nelayan terus menurun. Bahkan, menurut penuturan warga, hampir semua sekarang sudah bukan nelayan lagi.
Sesekali memang mereka masih ke laut, tetapi bukan untuk sumber utama pendapatan keluarga. Sebagian besar pendapat bersumber dari kebun, mulai dari kelapa dalam, pinang, pisang, dan sawit.
Berbagai komoditas ini mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat dibandingkan dengan mangrove. Sejauh pengamatan kami, masyarakat juga tidak menggunakannya untuk keperluan keseharian, misalnya untuk kayu bakar karena hampir semua rumah tangga sudah menggunakan bahan bakar gas yang ditempatkan dalam tabung.
Terakhir, pada temuan yang keenam, menurunnya nelayan tersebut ternyata berhubungan dengan meningkatnya abrasi. Pegiat lingkungan lokal memperkirakan dalam waktu satu tahun tingkat abrasi terjadi antara 5 sampai 10 meter. Hal ini memaksa warga memindahkan pemukiman mereka lebih jauh ke dalam.
Abrasi ini juga membuat mereka kesulitan menambatkan perahu karena jaraknya yang makin jauh. Pernah juga ada upaya melakukan penanaman kembali mangrove di lokasi-lokasi tertentu. Tapi program ini tidak berhasil. Bibit-bibit mangrove yang ditanam tak kuat menahan hantaman gelombang dan akhirnya hanyut terbawa arus.
Mengurai Persoalan Kehilangan Mangrove
Dalam menghadapi berbagai tantangan tehadap ekosistem mangrove, banyak yang mengngkat bahwa NbS mampu menghadirkan solusi yang bisa diterima untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertanyaannya ialah apakah memang demikian? Kami menggarisbawahi beberapa catatan yang perlu disorot untuk penerapan NbS di Sungai Sayang.
Pertama, untuk bisa menjadi solusi yang diterima tak cukup mengandalkan kebenaran saintifik atau pendekatan akademik. Dari diskusi dengan stakeholder di lapangan, menghasilkan pengetahuan saintifik adalah satu hal, dan membuatnya menjadi tindakan nyata merupakan hal lain yang berbeda. Jarak antar keduanya seringkali jauh.
Tapi meskipun hal ini tetap penting namun, yang kedua, NbS perlu untuk memahami dinamika relasi kuasa lokal, yang ini menjadi hal sangat mendasar dalam penerapannya karena harus berhubungan dengan banyak relasi sosial dan politik yang sudah ada sebelumnya dan biasanya bekerja dalam banyak aktivis sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal.
Analisis ketiga, NbS harus mampu menjadi pengatahuan kolektif dan untuk itu diperlukan upaya membangun narasi yang sensitif terhadap krisis sosial, ekonomi dan lingkungan setempat.
Dalam rumusan yang sederhana, untuk bisa diterma, NbS harus bisa membuktikan bahwa dirinya menjawab soal abrasi, perubahan sumber-sumber pendapatan, masalah sistem tenurial dan memperkuat solidaritas lokal yang sebelumnya sudah dibentuk oleh relasi kuasa para kepala parit. Semakin banyak aspek yang bisa diakomodir oleh NbS, semakin membuatnya punya daya implementasi yang lebih besar. Sulit dibayangkan akan mudah diterima jika hanya dikatakan bahwa NbS adalah solusi yang paling lingkungan dari lainnya.
Untuk itu, yang keempat, diperlukan produksi pengetahuan NbS secara konsisten dan berjangka panjang oleh pusat-pusat pengetahuan lokal agar tidak terkesan hanya sekedar proyek jangka pendek yang cepat menghilang.
Kami mendapati ada banyak sekali program penanaman mangrove oleh berbagai pihak, sebagiannya berhasil tapi sebagian besarnya tidak berkelanjutan. Persoalan mendasar dari semua ini adalah tidak ada upaya disursif yang massif untuk mengintegrasikan perlindungan mangrove dalam paradigma dan orientasi pembangunan daerah. Khususnys di Jambi paradigma masih dominan pertumbuhan ketimbang keberlanjutan. Dan dari sisi orientasi masih condong ke wilayah hulu, sedangkan wilayah hilir dianggap halaman belakang yang kurang diperhatikan.
Dalam menjadikan NbS sebagai solusi, yang terahir terkait dengan pertanyaan mengapa produksi pengetahuan mangrove tersebut sangat penting. Meskipun terletak di ujung pantai timur Jambi yang jauh, cerita mangrove Sungai Sayang tak bisa lepas dari sejauh mana mangrove dibicarakan di level pemerintahan yang lebih tinggi. Ada kemungkinan bahwa tak ada cerita unik soal kontribusi mangrove tehadap kehidupan masyarakat. Penelusuran kami terhadap hal ini, menunjukkan bahwa mangrove menempati posisi sangat minor dari diskursus pembangunan daerah.
Semua catatan yang kami soroti tersebut untuk mendorong NbS sebagai proses enviromentalisasi, bukan sekedar menempatkannya sebagai inovasi yang bersifat individual dan parsial. Secara teknis sudah tentu NbS bisa diterapkan. Namun untuk menjadi lebih berkelanjutan perlu mentransformasikannya menjadi kesadaran kolektif yang bisa diterima warga lokal sebagai bagian dari pemulihan krisis sosial ekologi.
*) Penulis adalah Kepala Sekolah Riset Satukata
Tulisan ini merupakan tulisan kedua dari tiga rangkaian tulisan mengenai upaya penerapan nature-based solution untuk mengatasi bencana ekologis yang terjadi di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa yang terletak terpencil itu menghadapi bencana ekologis yang diperparah oleh perubahan iklim. Sebagai luaran dari kegiatan penelitian nature-based solution yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia – UGM dengan dukungan FINCAPES.
Referensi:L
- Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016). Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. xiii + 97pp.
- Forsyth, Tim. 2003. Critical political ecology: the politic of environmental science. Routledge, Canada.
- Haeran. 2019. Tradisi Macerak Parek sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat suku Bugis di Tanjung Jabung Timur. Jurnal Sabda Volume 15, Nomor 2.
- Winston A. Asante, Emmanuel Acheampong, Kyereh Boateng, Jacob Adda. 2017. The implications of land tenure and ownership regimes on sustainable mangrove management and conservation in two Ramsar sites in Ghana. Journal of Forest Policy and Economics, Volume 85, Part 1.
- Appiah-Opoku, Seth, ed. 2020. ‘Land Use Change and Sustainability’. IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.7784
- Schmidt, Vivien A., 2008. Discursive Institutionalism: The Explanatory





